Periode 1966 hingga 1998 merupakan periode yang
memiliki ciri khas tersendiri dalam sejarah panjang Indonesia. Dalam rentang waktu tersebut,
Orde Baru lahir dan berkembang
dengan segala “keistimewaan” yang menyelimutinya,
selama tiga dekade lebih memimpin Indonesia.
Menurut Michael vatikiotis, merupakan suatu
periode kepemimpinan seorang penguasa yang paling lama dalam sejarah Asia
Tenggara modern.
David Bourchier
(dalam Harry
Aveling, 2003:1) memberikan suatu kesimpulan, bahwa apabila ditarik
benang merah ideologi selama pemerintahan Soeharto, maka konsepnya adalah
“ketertiban”. Dalam hal ini,
Soeharto mengencangkan stabilitas, ketertiban, dan kemanan sebagai “objek” dari
perkembangan itu sendiri, yaitu untuk membuat rakyat -secara fisik- merasa aman
dan tentram, bebas dari ketakutan dan ancaman.
Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam
upaya mengejar “ketertiban” selama bertahun-tahun, berbagai kebebasan telah
lenyap. Kepemimpinan Soeharto semakin otoriter, sistem politik semakin lama
semakin kaku (atau dikakukan?), di samping itu, militer
berusaha keras membangun diri untuk menjadi elemen kekuatan politik dominan di
negeri ini, tak tertandingi oleh kekuatan-kekuatan lainnya.
Dalam pelaksanannya, selain
mengurus hal-hal yang makro dalam negara, untuk melanggengkan kekuasaan, Orde
Baru juga “menertibkan” setiap pemikiran dan perbuatan individu. Di mana
ekspresi semakin sempit, opini atau pendapat pribadi terus menerus dicurigai,
dan bahkan diiringi ancaman hukuman, dengan penangkapan atau dipenjara.
Bencana
bagi penulis
Konsep “penertiban” Soeharto juga merambah ke dunia
sastra. Henk Maier –profesor bahasa melayu dari Universitas Leiden, Belanda-
mengatakan bahwa Soeharto dan aparat pemerintahannya telah menjadi bencana bagi
sebuah generasi penulis, merampok mereka dari kekuatan generatifnya, kekuatan
untuk menjadi saksi sejarah yang bisa mengabarkan pada dunia luar apa yang
sebenarnya terjadi di depan mata mereka.
Dalam situasi
yang demikian, Rendra bagaimanapun adalah seorang
sastrawan yang gigih menyuarakan kritik pada masa pemerintahan Orde Baru dan
sering menantang bahaya sepanjang tahun 70-an. Keluar masuk penjara adalah hal
yang biasa ketika kata dilawan dengan senjata, bahkan kuasa.
Ia pertama kali ditangkap pada Desember 1970, karena
ikut ambil bagian dalam “Renungan Malam” sebagai aksi menentang
kesewenang-wenangan pemerintah. Pada tahun 1973, ia ditangkap kembali akibat
pementasan drama Mastodon dan Burung
Kondor. Sebagai konsekuensi dari pementasan drama ini, Rendra dilarang
mengadakan pementasan lainnya di Yogyakarta sampai tahun 1977, karena keadaan
khusus yang terjadi di daerah.
Selain lewat drama, kritik Rendra terhadap
pemerintah juga hadir dalam puisi-puisinya di sepanjang tahun 1970-an. Bahasa
dalam puisi tersebut –yang kemudian dikumpulkan dalam buku puisi Potret Pembangunan dalam Puisi- tertuju
langsung dan jelas-jelas menampakkan seruan emosi si “pemberontak”. Sajak-sajak itu secara umum, mengkritik efek
dari industrialisasi, pendidikan, moral, dan lainnya terhadap keseimbangan
antara kemanusiaan dan alam, juga menyerang perilaku materialistis –tanpa
memikirkan kesejahteraan rakyat-.
Pada tahun 1971, setelah pengembaraan intelektualnya di Amerika,
Rendra mulai bisa melihat masalah sosial-politik-ekonomi secara sturuktual dan
menyeluruh di negeri ini. Untuk itu, ia
“terpaksa” harus rela melepaskan dirinya dari pesona misteri dan ambiguitas, yang selama ini lekat dengan puisi-puisinya.
Ia sadar gagasan, pesan, ide dan kritiknya
kali ini memerlukan sarana estetika yang lain. Metafora simbolistis dan
surealistis sudah tidak sesuai lagi. Yang diperlukan kali ini adalah
metafora-metafora baru yang plastis dan grafis.
Dengan metafora plastis dan grafis, dan dengan bahasa
yang transparan, sajak-sajak Rendra, jadi kurang kadar puitisnya. Hampir tampak
antipuitis, seperti kata A. Teeuw, bahwa sajak-sajak Rendra seperti “koran”.
Akan tetapi, memang Rendra menulis untuk dimengerti, bukan untuk menghidangkan
teka-teki.
Pada pemerintahan Orde Baru, karya sastra (puisi
pada khususnya) tidak dijadikan sebagai alat untuk memapankan kekuasaan.
Pemerintah lebih “senang” menggunakan agen-agen yang bergerak pada ranah
institusi, yang secara publik mempunyai kewenangan (Arif Hidayat, 2012: 164).
Sementara itu, puisi berada di “wilayah lain” yang tidak diinginkan.
Rezim Orde Baru sejatinya membolehkan penyair untuk
berekspresi asalkan dengan tidak mempunyai ideologi yang tidak mengkritik atau
bersebrangan dengan pemerintah. Oleh karenanya, wilayah religious, juga
pandangan tentang sufi menjadi bagian yang paling aman untuk dituliskan. Mereka
memilih menyampaikan wacana sufi karena ada dalam ranah yang tidak mengusik
pemertintah. Di satu
sisi posisi mereka aman dalam membuat sejarah sastra baru, di sisi lain juga
aman untuk mendekati publik.
oleh: Aan Herdiana

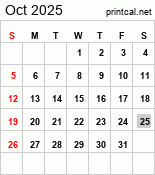
0 komentar:
Posting Komentar